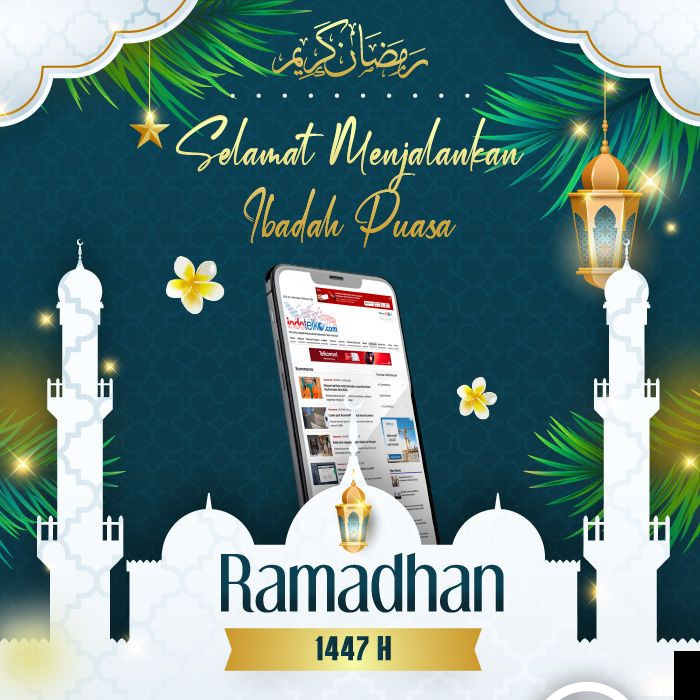Kuota internet hangus, siapa yang diuntungkan?
04:00:00 | 15 Jun 2025

Isu hangusnya kuota internet prabayar menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini.
Awalnya, ada temuan dari Indonesian Audit Watch (IAW) yang mengecam praktik kuota internet yang hangus akibat masa aktif sebagai "sampah digital termahal di dunia".
Dalam rilis resminya, IAW menyebut nilai kerugian konsumen mencapai Rp613 triliun sejak 2010 hingga 2024 akibat kuota tak terpakai yang dimusnahkan operator telekomunikasi secara sepihak.
Dalam kajian IAW, kuota internet merupakan aset digital yang dibeli konsumen, bukan sewa waktu. IAW menilai ada indikasi pelanggaran Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang itikad baik kontrak.
IAW membandingkan dengan Australia dan Malaysia yang memberlakukan rollover kuota, sementara di Indonesia, kuota yang telah dibayar penuh justru dihanguskan. Padahal, menurut Pasal 1457 KUHPerdata, transaksi kuota termasuk jual-beli barang digital.
IAW menuding operator telekomunikasi melakukan tiga pelanggaran:
1. Klausul Baku Merugikan (Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen).
2. Pendapatan Palsu, jika kuota hangus tidak dicatat sebagai liabilitas (Pasal 3 UU Tipikor).
3. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena merugikan hak ekonomi konsumen. Untuk itu IAW mendesak adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan operator telekomunikasi sejak 2010 dan pembentukan Satgas Tipikor Digital oleh KPK dan Kejagung untuk menyelidiki aliran dana kuota hangus. terakhir, Judicial Review terhadap Permenkominfo No. 5/2021 yang dianggap melegalkan praktik ini. Tanggapan ATSI
Sementara Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa praktik tersebut legal dan sesuai regulasi. Menurut ATSI, penetapan masa aktif dan penghapusan kuota setelah kadaluarsa merupakan praktik wajar, bahkan lazim diterapkan di industri seluler global. Organisasi ini merujuk pada Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan. Selain itu, pulsa dan kuota dianggap sebagai barang konsumsi, bukan alat pembayaran sah atau uang elektronik, sehingga tidak tunduk pada kewajiban refund atau pengembalian saldo. Penerapan masa aktif dinilai selaras dengan praktik di sektor lain, seperti tiket transportasi atau voucher diskon. Namun persoalannya tak sesederhana soal legalitas, tetapi apakah praktik ini adil dan transparan dari sisi perlindungan konsumen dan pelaporan keuangan? Secara akuntansi, penggunaan sistem prabayar memang tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK 72 tentang “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”. Di sana diatur bahwa uang yang diterima di awal (misalnya saat konsumen membeli paket data) harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, dan baru diakui sebagai pendapatan ketika layanan digunakan. Dalam konteks kuota yang tidak terpakai hingga masa aktif berakhir, maka nilai tersebut bisa dikategorikan sebagai breakage revenue, dan tetap harus dicatat serta diungkapkan secara akuntabel. Telusur terhadap laporan keuangan operator besar seperti Telkomsel (via Telkom Indonesia), XL Axiata, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Smartfren, menunjukkan bahwa mereka telah mencantumkan akun “deferred revenue” dan menjelaskan pengakuan pendapatan dari layanan prabayar. Telkom, misalnya, menyebutkan bahwa pendapatan dari kuota yang tidak digunakan akan diakui saat masa aktif habis. Hal serupa juga dinyatakan XL dan Indosat, meski tidak selalu merinci angka breakage secara eksplisit. Di sinilah letak masalah: sekalipun diakui, tingkat transparansi antar operator berbeda-beda, sehingga publik sulit menilai sejauh mana nilai kuota hangus menjadi pendapatan perusahaan dan apakah seluruhnya telah dikenakan pajak sesuai aturan. Perilaku Konsumen
Lebih jauh lagi, perdebatan ini menjadi relevan jika kita melihat pola konsumsi aktual pengguna internet Indonesia. Menurut laporan Ericsson Mobility Report 2024 dan data dari Opensignal, rata-rata penggunaan data seluler masyarakat Indonesia per bulan berada di kisaran 1017 GB. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna masih tergolong light to moderate user, hanya menggunakan 1020 GB per bulan. Banyak dari mereka juga mengandalkan koneksi Wi-Fi di rumah atau kantor. Disisi lain, banyak operator menawarkan paket data bulanan dengan kuota hingga 30, 50, bahkan 100 GB. Jika kuota yang ditawarkan jauh melampaui kebutuhan mayoritas pengguna, dan kelebihannya hangus begitu saja setiap bulan, tentu pertanyaannya, apakah ini pemenuhan kebutuhan nyata atau sekadar strategi pemasaran operator yang tak disadari konsumen? Dalam kenyataan, literasi digital masyarakat Indonesia masih belum memadai. Riset Katadata Insight Center dan Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan pemahaman terhadap fitur paket, masa aktif, dan rollover masih rendah, terutama di kalangan pengguna prabayar di daerah. Jika kita kembali pada analogi yang digunakan ATSI, yaitu membandingkan kuota dengan tiket pesawat atau voucher diskon, maka perlu diingat bahwa pembeli tiket tahu pasti tanggal dan jam penerbangan. Pembeli voucher tahu masa berlaku yang terbatas. Tapi pembeli paket data sering kali tidak sadar bahwa 2030 GB kuota mereka bisa lenyap dalam 30 hari, padahal belum dipakai 10 GB pun. Transparansi informasi bukan hanya soal “dicantumkan”, tapi juga “mudah dimengerti dan terlihat”. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini menjadi krusial. Apalagi jika industri telah mengakui bahwa kuota yang hangus adalah pendapatan, maka secara moral dan fiskal, seharusnya ada pelaporan yang lebih akuntabel kepada publik. Bila breakage revenue sudah dicatat, apakah pemerintah juga mendapatkan bagian pajaknya? Bila tidak, apakah ini celah fiskal? Lebih luas lagi, kita juga bisa berkaca ke negara lain. Di Singapura, operator seperti Singtel dan M1 menawarkan paket rollover atau data pooling bagi keluarga. Di Malaysia, CelcomDigi memberi opsi pembelian data yang tak hangus selama 365 hari. Beberapa operator bahkan menawarkan add-on gratis agar kuota bisa dipakai lebih lama, bukan hangus otomatis. Artinya, praktik internasional bukan soal “hangus adalah standar”, melainkan soal fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan nyata pengguna. Di titik ini, langkah korektif perlu segera dilakukan. Regulator, seperti Komdigi dan Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN) bisa mendorong agar opsi rollover menjadi fitur default, bukan layanan premium, operator mengungkapkan nilai breakage di laporan keuangan secara terbuka, dan literasi digital mengenai pembelian paket dan masa aktif diperkuat lewat kolaborasi industri dan masyarakat sipil. Industri telekomunikasi Indonesia telah berkembang pesat, melayani lebih dari 210 juta pengguna, menjadi tulang punggung transformasi digital nasional.
Tapi keberlanjutan industri tidak bisa hanya ditopang oleh logika komersial. Ia juga harus menjunjung etika bisnis, keadilan konsumen, dan akuntabilitas publik. Apalagi di era ekonomi digital seperti sekarang, kuota internet bukan lagi sekadar barang konsumsi. Ia telah menjadi hak dasar masyarakat.
Dan ketika hak itu perlahan hilang, entah karena expired date atau desain paket yang tak masuk akal, maka yang hangus bukan hanya kuota, tapi juga kepercayaan.
@IndoTelko
Baca juga :
•
•
•
1. Klausul Baku Merugikan (Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen).
2. Pendapatan Palsu, jika kuota hangus tidak dicatat sebagai liabilitas (Pasal 3 UU Tipikor).
3. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena merugikan hak ekonomi konsumen. Untuk itu IAW mendesak adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan operator telekomunikasi sejak 2010 dan pembentukan Satgas Tipikor Digital oleh KPK dan Kejagung untuk menyelidiki aliran dana kuota hangus. terakhir, Judicial Review terhadap Permenkominfo No. 5/2021 yang dianggap melegalkan praktik ini. Tanggapan ATSI
Sementara Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa praktik tersebut legal dan sesuai regulasi. Menurut ATSI, penetapan masa aktif dan penghapusan kuota setelah kadaluarsa merupakan praktik wajar, bahkan lazim diterapkan di industri seluler global. Organisasi ini merujuk pada Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan. Selain itu, pulsa dan kuota dianggap sebagai barang konsumsi, bukan alat pembayaran sah atau uang elektronik, sehingga tidak tunduk pada kewajiban refund atau pengembalian saldo. Penerapan masa aktif dinilai selaras dengan praktik di sektor lain, seperti tiket transportasi atau voucher diskon. Namun persoalannya tak sesederhana soal legalitas, tetapi apakah praktik ini adil dan transparan dari sisi perlindungan konsumen dan pelaporan keuangan? Secara akuntansi, penggunaan sistem prabayar memang tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK 72 tentang “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”. Di sana diatur bahwa uang yang diterima di awal (misalnya saat konsumen membeli paket data) harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, dan baru diakui sebagai pendapatan ketika layanan digunakan. Dalam konteks kuota yang tidak terpakai hingga masa aktif berakhir, maka nilai tersebut bisa dikategorikan sebagai breakage revenue, dan tetap harus dicatat serta diungkapkan secara akuntabel. Telusur terhadap laporan keuangan operator besar seperti Telkomsel (via Telkom Indonesia), XL Axiata, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Smartfren, menunjukkan bahwa mereka telah mencantumkan akun “deferred revenue” dan menjelaskan pengakuan pendapatan dari layanan prabayar. Telkom, misalnya, menyebutkan bahwa pendapatan dari kuota yang tidak digunakan akan diakui saat masa aktif habis. Hal serupa juga dinyatakan XL dan Indosat, meski tidak selalu merinci angka breakage secara eksplisit. Di sinilah letak masalah: sekalipun diakui, tingkat transparansi antar operator berbeda-beda, sehingga publik sulit menilai sejauh mana nilai kuota hangus menjadi pendapatan perusahaan dan apakah seluruhnya telah dikenakan pajak sesuai aturan. Perilaku Konsumen
Lebih jauh lagi, perdebatan ini menjadi relevan jika kita melihat pola konsumsi aktual pengguna internet Indonesia. Menurut laporan Ericsson Mobility Report 2024 dan data dari Opensignal, rata-rata penggunaan data seluler masyarakat Indonesia per bulan berada di kisaran 1017 GB. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna masih tergolong light to moderate user, hanya menggunakan 1020 GB per bulan. Banyak dari mereka juga mengandalkan koneksi Wi-Fi di rumah atau kantor. Disisi lain, banyak operator menawarkan paket data bulanan dengan kuota hingga 30, 50, bahkan 100 GB. Jika kuota yang ditawarkan jauh melampaui kebutuhan mayoritas pengguna, dan kelebihannya hangus begitu saja setiap bulan, tentu pertanyaannya, apakah ini pemenuhan kebutuhan nyata atau sekadar strategi pemasaran operator yang tak disadari konsumen? Dalam kenyataan, literasi digital masyarakat Indonesia masih belum memadai. Riset Katadata Insight Center dan Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan pemahaman terhadap fitur paket, masa aktif, dan rollover masih rendah, terutama di kalangan pengguna prabayar di daerah. Jika kita kembali pada analogi yang digunakan ATSI, yaitu membandingkan kuota dengan tiket pesawat atau voucher diskon, maka perlu diingat bahwa pembeli tiket tahu pasti tanggal dan jam penerbangan. Pembeli voucher tahu masa berlaku yang terbatas. Tapi pembeli paket data sering kali tidak sadar bahwa 2030 GB kuota mereka bisa lenyap dalam 30 hari, padahal belum dipakai 10 GB pun. Transparansi informasi bukan hanya soal “dicantumkan”, tapi juga “mudah dimengerti dan terlihat”. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini menjadi krusial. Apalagi jika industri telah mengakui bahwa kuota yang hangus adalah pendapatan, maka secara moral dan fiskal, seharusnya ada pelaporan yang lebih akuntabel kepada publik. Bila breakage revenue sudah dicatat, apakah pemerintah juga mendapatkan bagian pajaknya? Bila tidak, apakah ini celah fiskal? Lebih luas lagi, kita juga bisa berkaca ke negara lain. Di Singapura, operator seperti Singtel dan M1 menawarkan paket rollover atau data pooling bagi keluarga. Di Malaysia, CelcomDigi memberi opsi pembelian data yang tak hangus selama 365 hari. Beberapa operator bahkan menawarkan add-on gratis agar kuota bisa dipakai lebih lama, bukan hangus otomatis. Artinya, praktik internasional bukan soal “hangus adalah standar”, melainkan soal fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan nyata pengguna. Di titik ini, langkah korektif perlu segera dilakukan. Regulator, seperti Komdigi dan Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN) bisa mendorong agar opsi rollover menjadi fitur default, bukan layanan premium, operator mengungkapkan nilai breakage di laporan keuangan secara terbuka, dan literasi digital mengenai pembelian paket dan masa aktif diperkuat lewat kolaborasi industri dan masyarakat sipil. Industri telekomunikasi Indonesia telah berkembang pesat, melayani lebih dari 210 juta pengguna, menjadi tulang punggung transformasi digital nasional.
Artikel Terkait
-
 Editorial - 04:00:00 | 15 Feb 2026Pembangunan kabel optik kerap terjerat aturan lokal yang mahal dan tumpang tindih
Editorial - 04:00:00 | 15 Feb 2026Pembangunan kabel optik kerap terjerat aturan lokal yang mahal dan tumpang tindih -
 Editorial - 04:00:00 | 08 Feb 2026Kasus Jie Wo Rui di China harus menjadi pelajaran dalam berinvestasi di era digital
Editorial - 04:00:00 | 08 Feb 2026Kasus Jie Wo Rui di China harus menjadi pelajaran dalam berinvestasi di era digital
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories