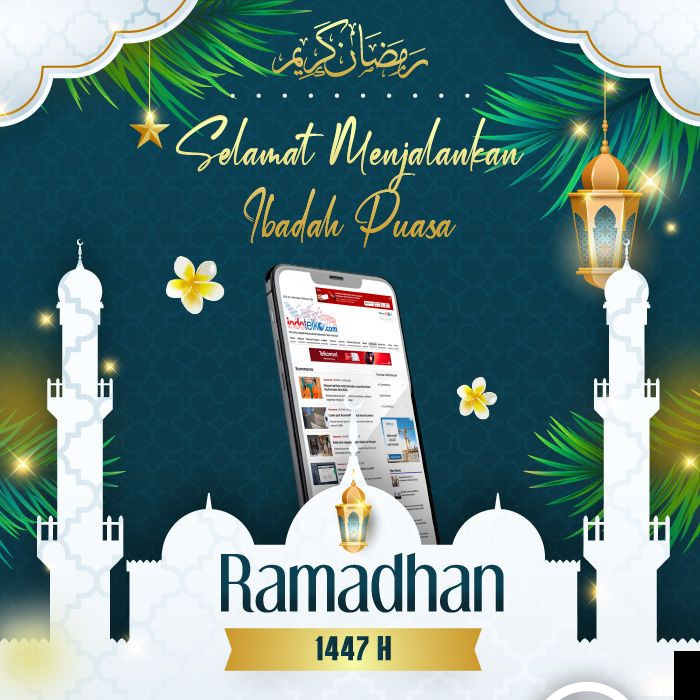Ironi dibalik ramainya data center global di Indonesia
04:00:00 | 08 Jun 2025

Microsoft resmi meluncurkan Indonesia Central Cloud Region pada Selasa, (28/05) lalu. Kehadiran data center pertama Microsoft di Indonesia ini menjadi komitmen perusahaan dalam bekerjasama dan berkontribusi dengan pemerintah Indonesia setelah kurang lebih 30 tahun hadir di Indonesia.
Pemerintah menyambut dengan suka cita. Nilai investasinya fantastis, sekitar Rp27 triliun, dan dampaknya diklaim bisa menyumbang Rp41 triliun ke ekonomi nasional, menciptakan hingga 60 ribu lapangan kerja.
Namun di balik euforia ini, ada pertanyaan yang patut direnungkan. Apakah kita hanya bangga menjadi tuan rumah yang baik, atau kita benar-benar sedang membangun kedaulatan digital nasional?
Pertanyaan ini bukan soal sentimen anti investasi asing. Justru sebaliknya, kita ingin memastikan bahwa kehadiran investor asing, apalagi raksasa teknologi dunia, bukan sekadar menghadirkan gedung dan kabel, tapi juga membawa nilai tambah yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan strategis bangsa.
Siapa Diuntungkan?
Bayangkan sebuah pusat data seperti pabrik besar. Ia butuh lahan luas, bangunan kokoh, sistem kelistrikan yang andal, pendingin super, serta koneksi data berkecepatan tinggi. Seluruh infrastruktur itu jelas memerlukan investasi besar. Di Indonesia, harga tanah di kawasan industri seperti Cikarang atau Karawang bisa mencapai Rp24 juta per meter persegi. Pusat data hyperscale biasanya berdiri di atas 5 hingga 10 hektar, dengan biaya konstruksi mencapai lebih dari US$7 juta untuk setiap megawatt kapasitas IT. Ini semua tentu melibatkan kontraktor lokal, produsen baja, pemasok AC industri, hingga insinyur listrik Indonesia. Nilai ekonomi lokalnya nyata. Tapi semua itu adalah belanja satu kali alias belaja modal yang selesai setelah gedung berdiri dan mesin menyala. Lalu datang tagihan listrik. Dalam pusat data, listrik bukan sekadar kebutuhan operasional, tapi darah kehidupan. Rata-rata, 4060% biaya operasional pusat data berasal dari listrik. Tarif industri PLN berada di kisaran Rp1.100 hingga Rp1.500 per kWh. Jadi setiap megawatt yang dikonsumsi berarti miliaran rupiah mengalir setiap bulan—sebuah nilai besar, tapi tetap bersifat infrastruktur dasar. Dari titik ini, mulai terlihat perbedaan mencolok antara siapa yang membangun dan siapa yang menikmati. Karena begitu pusat data aktif, nilai tambahnya justru berpindah ke lapisan yang tak terlihat oleh mata telanjang yakni platform digital. Dalam kasus Microsoft, perusahaan tidak hanya membangun gudang server. Mereka membawa seluruh layanannya seperti Azure untuk komputasi awan, Copilot untuk AI produktivitas, hingga OpenAI API untuk kecerdasan buatan canggih. Semua layanan ini tinggal diklik oleh pengguna, dan tagihannya langsung mengalir, bukan ke perusahaan lokal, melainkan ke sistem billing global milik Microsoft. Posisi Indonesia
Jika ditelusuri lebih jauh, nilai tambah terbesar dari pusat data justru ada di lapisan layanan digital, bukan di bangunan atau listriknya. Azure, misalnya, memungkinkan pengguna Indonesia menyimpan data, membangun aplikasi, mengakses AI, hingga menjalankan proses bisnis dalam skala besar. Tapi semua proses ini dikendalikan dari arsitektur yang kita tidak miliki. Kita menyewa, bukan menguasai. Ironisnya, bahkan lalu lintas data antar layanan Microsoft, misalnya transfer file dari Jakarta ke Singapura atau dari zona satu ke zona lain, dikenai biaya kepada pengguna. Bandwidth internal milik mereka pun bisa menjadi ladang bisnis tersendiri. Sementara kita sebagai tuan rumah hanya dapat “menonton” sambil menyuplai listrik dan menjaga suhu tetap dingin. Tentu, ada manfaat jangka pendek bagi Indonesia seperti pelatihan bagi talenta lokal, kerja sama riset, hingga peluang kerja baru. Tapi mari jujur, berapa banyak engineer Indonesia yang terlibat dalam pembangunan platform Microsoft? Apakah mereka hanya diberi pelatihan pengguna, atau benar-benar dilibatkan dalam pengembangan teknologi? Jangan Diam
Kita sedang menghadapi tantangan serius. Semakin banyak layanan digital Indonesia, baik pemerintah, pendidikan, keuangan, hingga startup, bergantung pada platform milik asing. Sekali masuk, sulit keluar. Inilah yang disebut vendor lock-in. Dan begitu sistem publik dibangun di atas platform asing, maka kontrol strategisnya ikut berpindah. Di era digital, data dan kecerdasan buatan bukan sekadar alat bantu. Ia telah menjadi alat kendali ekonomi dan geopolitik. Negara yang tak mampu mengelola data dan AI-nya sendiri akan terus menjadi pengguna, bukan penentu. Kita mungkin merasa bangga sebagai tuan rumah pusat data, tapi nilai tambah sebenarnya justru mengalir ke luar negeri, setiap detik, dalam bentuk uang digital. Jangan Puas
Indonesia tidak boleh hanya puas menjadi “kost-an” digital bagi platform global. Pemerintah dan regulator perlu mulai menyusun kebijakan yang mengunci nilai tambah di dalam negeri, antara lain: Pertama, wajibkan transfer teknologi secara nyata. Setiap pusat data asing harus membuka ruang co-development, bukan hanya skema reseller atau pelatihan dasar. Bangun ekosistem developer lokal yang punya akses pada teknologi inti, bukan sekadar pengguna dashboard. Kedua, tegaskan prinsip kedaulatan data dan AI. Data strategis nasional wajib diproses secara lokal, dengan model AI yang dapat diaudit. Jangan biarkan algoritma asing mengatur cara kita mengambil keputusan publik tanpa pengawasan. Ketiga, dorong interoperabilitas dan netralitas cloud. Jangan biarkan pemerintah dan startup kita tergantung pada satu platform. Terapkan standar terbuka dan kebijakan multi-cloud agar ekosistem digital tetap kompetitif dan sehat. Keempat, beri insentif bagi pelaku teknologi lokal. Platform lokal yang mengembangkan komputasi awan, edge computing, hingga layanan AI perlu diberikan ruang dan dukungan—baik dari sisi fiskal, pengadaan, maupun inkubasi. Dan yang tak kalah penting, audit secara transparan nilai ekonomi digital kita. Berapa besar uang rakyat Indonesia yang mengalir ke luar negeri lewat langganan cloud, API, dan lisensi platform. Transparansi ini penting agar kita tahu, apakah ekonomi digital benar-benar menyejahterakan bangsa, atau hanya segelintir penyedia platform global
Ramainya pusat data milik pemain global berdiri megah di atas tanah kita memang simbol kemajuan. Tapi jangan sampai kita terlena hanya karena kabel tersambung dan server menyala. Hal utama dari infrastruktur adalah siapa yang mengendalikan teknologi di atasnya.
Indonesia harus naik kelas. Jangan hanya menjadi pengguna, tapi juga pembangun. Jangan hanya menjadi pasar, tapi juga pemilik. Karena dalam dunia digital, kedaulatan bukan lagi ditentukan oleh siapa yang punya tanah, tapi siapa yang menguasai data dan algoritma.
@IndoTelko
Baca juga :
•
•
•
Bayangkan sebuah pusat data seperti pabrik besar. Ia butuh lahan luas, bangunan kokoh, sistem kelistrikan yang andal, pendingin super, serta koneksi data berkecepatan tinggi. Seluruh infrastruktur itu jelas memerlukan investasi besar. Di Indonesia, harga tanah di kawasan industri seperti Cikarang atau Karawang bisa mencapai Rp24 juta per meter persegi. Pusat data hyperscale biasanya berdiri di atas 5 hingga 10 hektar, dengan biaya konstruksi mencapai lebih dari US$7 juta untuk setiap megawatt kapasitas IT. Ini semua tentu melibatkan kontraktor lokal, produsen baja, pemasok AC industri, hingga insinyur listrik Indonesia. Nilai ekonomi lokalnya nyata. Tapi semua itu adalah belanja satu kali alias belaja modal yang selesai setelah gedung berdiri dan mesin menyala. Lalu datang tagihan listrik. Dalam pusat data, listrik bukan sekadar kebutuhan operasional, tapi darah kehidupan. Rata-rata, 4060% biaya operasional pusat data berasal dari listrik. Tarif industri PLN berada di kisaran Rp1.100 hingga Rp1.500 per kWh. Jadi setiap megawatt yang dikonsumsi berarti miliaran rupiah mengalir setiap bulan—sebuah nilai besar, tapi tetap bersifat infrastruktur dasar. Dari titik ini, mulai terlihat perbedaan mencolok antara siapa yang membangun dan siapa yang menikmati. Karena begitu pusat data aktif, nilai tambahnya justru berpindah ke lapisan yang tak terlihat oleh mata telanjang yakni platform digital. Dalam kasus Microsoft, perusahaan tidak hanya membangun gudang server. Mereka membawa seluruh layanannya seperti Azure untuk komputasi awan, Copilot untuk AI produktivitas, hingga OpenAI API untuk kecerdasan buatan canggih. Semua layanan ini tinggal diklik oleh pengguna, dan tagihannya langsung mengalir, bukan ke perusahaan lokal, melainkan ke sistem billing global milik Microsoft. Posisi Indonesia
Jika ditelusuri lebih jauh, nilai tambah terbesar dari pusat data justru ada di lapisan layanan digital, bukan di bangunan atau listriknya. Azure, misalnya, memungkinkan pengguna Indonesia menyimpan data, membangun aplikasi, mengakses AI, hingga menjalankan proses bisnis dalam skala besar. Tapi semua proses ini dikendalikan dari arsitektur yang kita tidak miliki. Kita menyewa, bukan menguasai. Ironisnya, bahkan lalu lintas data antar layanan Microsoft, misalnya transfer file dari Jakarta ke Singapura atau dari zona satu ke zona lain, dikenai biaya kepada pengguna. Bandwidth internal milik mereka pun bisa menjadi ladang bisnis tersendiri. Sementara kita sebagai tuan rumah hanya dapat “menonton” sambil menyuplai listrik dan menjaga suhu tetap dingin. Tentu, ada manfaat jangka pendek bagi Indonesia seperti pelatihan bagi talenta lokal, kerja sama riset, hingga peluang kerja baru. Tapi mari jujur, berapa banyak engineer Indonesia yang terlibat dalam pembangunan platform Microsoft? Apakah mereka hanya diberi pelatihan pengguna, atau benar-benar dilibatkan dalam pengembangan teknologi? Jangan Diam
Kita sedang menghadapi tantangan serius. Semakin banyak layanan digital Indonesia, baik pemerintah, pendidikan, keuangan, hingga startup, bergantung pada platform milik asing. Sekali masuk, sulit keluar. Inilah yang disebut vendor lock-in. Dan begitu sistem publik dibangun di atas platform asing, maka kontrol strategisnya ikut berpindah. Di era digital, data dan kecerdasan buatan bukan sekadar alat bantu. Ia telah menjadi alat kendali ekonomi dan geopolitik. Negara yang tak mampu mengelola data dan AI-nya sendiri akan terus menjadi pengguna, bukan penentu. Kita mungkin merasa bangga sebagai tuan rumah pusat data, tapi nilai tambah sebenarnya justru mengalir ke luar negeri, setiap detik, dalam bentuk uang digital. Jangan Puas
Indonesia tidak boleh hanya puas menjadi “kost-an” digital bagi platform global. Pemerintah dan regulator perlu mulai menyusun kebijakan yang mengunci nilai tambah di dalam negeri, antara lain: Pertama, wajibkan transfer teknologi secara nyata. Setiap pusat data asing harus membuka ruang co-development, bukan hanya skema reseller atau pelatihan dasar. Bangun ekosistem developer lokal yang punya akses pada teknologi inti, bukan sekadar pengguna dashboard. Kedua, tegaskan prinsip kedaulatan data dan AI. Data strategis nasional wajib diproses secara lokal, dengan model AI yang dapat diaudit. Jangan biarkan algoritma asing mengatur cara kita mengambil keputusan publik tanpa pengawasan. Ketiga, dorong interoperabilitas dan netralitas cloud. Jangan biarkan pemerintah dan startup kita tergantung pada satu platform. Terapkan standar terbuka dan kebijakan multi-cloud agar ekosistem digital tetap kompetitif dan sehat. Keempat, beri insentif bagi pelaku teknologi lokal. Platform lokal yang mengembangkan komputasi awan, edge computing, hingga layanan AI perlu diberikan ruang dan dukungan—baik dari sisi fiskal, pengadaan, maupun inkubasi. Dan yang tak kalah penting, audit secara transparan nilai ekonomi digital kita. Berapa besar uang rakyat Indonesia yang mengalir ke luar negeri lewat langganan cloud, API, dan lisensi platform. Transparansi ini penting agar kita tahu, apakah ekonomi digital benar-benar menyejahterakan bangsa, atau hanya segelintir penyedia platform global
Artikel Terkait
-
 Editorial - 04:00:00 | 15 Feb 2026Pembangunan kabel optik kerap terjerat aturan lokal yang mahal dan tumpang tindih
Editorial - 04:00:00 | 15 Feb 2026Pembangunan kabel optik kerap terjerat aturan lokal yang mahal dan tumpang tindih -
 Editorial - 04:00:00 | 08 Feb 2026Kasus Jie Wo Rui di China harus menjadi pelajaran dalam berinvestasi di era digital
Editorial - 04:00:00 | 08 Feb 2026Kasus Jie Wo Rui di China harus menjadi pelajaran dalam berinvestasi di era digital
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories